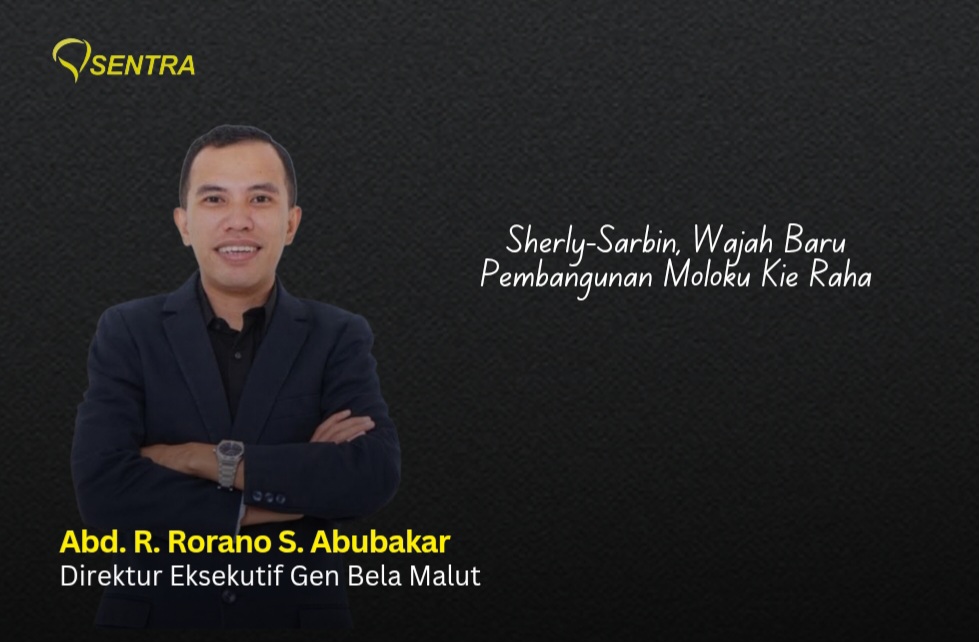Oleh:
Abd. R. Rorano S. Abubakar (Direktur Eksekutif Gen Muda Bela)
Moloku Kie Raha, sebagai representasi budaya dan sejarah Maluku Utara, tengah menghadapi babak baru dalam pembangunan. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) yang secara resmi akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Kamis 20 Februari 2025, tentu hadir dengan visi yang diklaim mampu membawa perubahan signifikan bagi daerah ini. Namun, pembangunan yang dicanangkan bukan hanya sekadar infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kebudayaan yang menjadi identitas utama masyarakat Moloku Kie Raha.
Dalam konteks yang lebih spesifik, terutama terkait pembangunan pada aspek kebudayaan, maka hemat saya, yang penting untuk diproyeksikan ialah membuka ruang komunikasi yang terbuka dan intensif dengan para pemangku kebijakan atau otoritas adat, yakni keempat wilayah kesultanan di Maluku Utara. Di samping simpul-simpul komunitas masyarakat adat (indegenous people) yang tersebar di hampir di semua wilayah Halmahera.
Hal tersebut patut dipertimbangkan sebagai disain pembangunan dalam lanskap kebudayaan oleh Sherly-Sarbin, mengingat kurang-lebih pada tiga periode pemerintahan provinsi Maluku Utara sebelumnya, upaya ke arah pembangunan kebudayaan dengan mempertimbangkan kebijakan adat masih sangat minim. Kondisi demikian justru berdampak serius pada melebarnya kesenjangan (gap) di antara pemerintahan negara dengan simpul atau otoritas adat yang tak jarang memunculkan konflik sosial yang tak berkesudahan disebabkan oleh pencaplokan ruang hidup (hutan, laut, tanah ulayat, dlsb).
Lagipula, kebudayaan tidak mesti dimaknai secara artifisial pada batasnya yang seremonial semata. Lebih dari itu, kebudayaan menyangkut dengan mengenal lalu kemudian mengalami kebudayaan itu sendiri sebagai semacam ‘piranti’ atau ‘pintu masuk’ menuju kemanusiaan. Sebuah bangunan kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai sebuah laboratorium kebudayaan, Moloku Kie Raha mestinya lebih fleksibel dibangun dengan ciri khas seperti ini. Pembangunan yang bertumpu pada akar-akar kearifan lokal (local wisdom) orang-orang Moloku Kie Raha sendiri. Pembangunan yang menempatkan adat se atoran sebagai prisma demi terwujudnya masyarakat adil makmur.
Tentu sebagai catatan pembuka, selaku seorang ngofa se dano dari leluhur negeri kepulauan rempah ini, saya menaruh rasa optimis pada kepemimpinan yang baru di Provinsi Maluku Utara dengan dua nahkoda barunya bernama Sherly-Sarbin. Tanpa menunggu waktu dilantik secara resmi pada 20 Februari 2025 besok, catatan ini merupakan rentetan catatan yang akan meneropong terus ke mana kedua nahkoda tersebut berlayar.
Pembangunan Politik-Kebudayaan: Sebuah Titik temu Perspektif
Pembangunan tanpa kebudayaan adalah proyek kosong yang kehilangan ruhnya. Sejarah telah membuktikan bahwa Moloku Kie Raha adalah wilayah dengan akar budaya yang kuat, dari Kesultanan Ternate dan Tidore hingga nilai-nilai lokal (local values) seperti Fagogoru di “Tiga Negeri” Gamrange di Halmahera, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan Sherly-Sarbin, menurut hemat saya, kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kearifan lokal (local wisdom), bukan hanya mengikuti pola modernisasi yang seragam dan cenderung mengabaikan identitas budaya.
Kebudayaan di Maluku Utara tidak hanya soal adat dan tradisi, tetapi juga cara masyarakat memahami dan menjalankan kehidupan sosial, politik, serta ekonomi mereka. Jika pembangunan hanya menitikberatkan pada investasi besar dan proyek-proyek industri tanpa mempertimbangkan dampak sosial-budaya, maka masyarakat adat dan komunitas lokal berisiko tersingkir dari proses pembangunan itu sendiri.
Konteks pembangunan seperti ini yang telah lama dirindukan oleh masyarakat Maluku Utara di tengah arus pembangunan modern yang semakin menguat. Atau dengan lain kalimat, pembangunan yang ditopang dengan pemanfaatan sebesar-besarnya teknologi dan industri. Tentu ruang ini lebih bisa dimaknai sebagai titik temu perspektif. Sebab, tidak harus ada pertentangan yang membabi buta terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan modern itu. Akan tetapi di sisi yang lain, tidak mesti lantas terlepas atau meninggalkan nilai atau identitas lokal yang telah eksis bahkan melampaui usia kemerdekaan negara ini dan telah menjadi karakter atau ciri khas kita sebagai manusia Moloku Kie Raha.
Jika titik temu perspektif ini bisa diterapkan dengan harmonis dalam proyeksi pembangunan pemerintahan provinsi Maluku Utara, setidaknya selama 5 (lima) tahun ke depan, saya yakin dan semakin optimis bahwa wajah pemerintahan Maluku Utara di bawah arahan dua nahkoda Sherly-Sarbin ini akan terus berlayar seimbang dan fokus ke tujuan pembangunan itu sendiri. Meskipun kerap tak bisa dipungkiri akan selalu ada terpaan badai dan gelombang yang datang sewaktu-waktu.
Politik-Kebudayaan sebagai Pendekatan Pembangunan
Nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dijadikan acuan dalam interaksi sosial perlu dikaji dalam merencanakan sebuah pembangunan. lebih-lebih bila pembangunan tersebut langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dove (1988) mengemukakan bahwa aspek pranata kebudayaan tersebut harus pula diperhitungkan karena sesungguhnya pranata-pranata kebudayaan terkait erat dan secara langsung menunjang proses sosial, ekonomi dan ekologis masyarakat secara mendasar dalam kehidupannya dan yang secara operasional telah mereka praktekkan sejak dahulu.
Pembangunan politik-kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa. Karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya menanggalkan martabat dan integritas manusia. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak menjadi alat marginalisasi, melainkan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan top-down (atas ke bawah) yang terlalu dominan sering kali membuat masyarakat hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri. Sebaliknya, pendekatan berbasis budaya dan partisipasi masyarakat atau bottom-up (bawah ke atas) akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berakar pada kebutuhan dan aspirasi lokal.
Sherly-Sarbin, sebagai wajah baru pembangunan di Moloku Kie Raha, memiliki peluang untuk menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Keberpihakan terhadap kebudayaan bisa diwujudkan melalui kebijakan pendidikan berbasis lokal, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta perlindungan terhadap situs-situs sejarah yang menjadi warisan leluhur.
Pembangunan di Moloku Kie Raha tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang berdiri atau seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa jauh budaya dan identitas lokal tetap hidup dan berkembang. Politik kebudayaan dalam pemerintahan Sherly-Sarbin harus mampu menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek dari kebijakan yang ditentukan dari luar. Dengan demikian, wajah baru pembangunan Moloku Kie Raha bukan hanya tentang modernisasi, tetapi juga tentang keberlanjutan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sukur dofu-dofu!