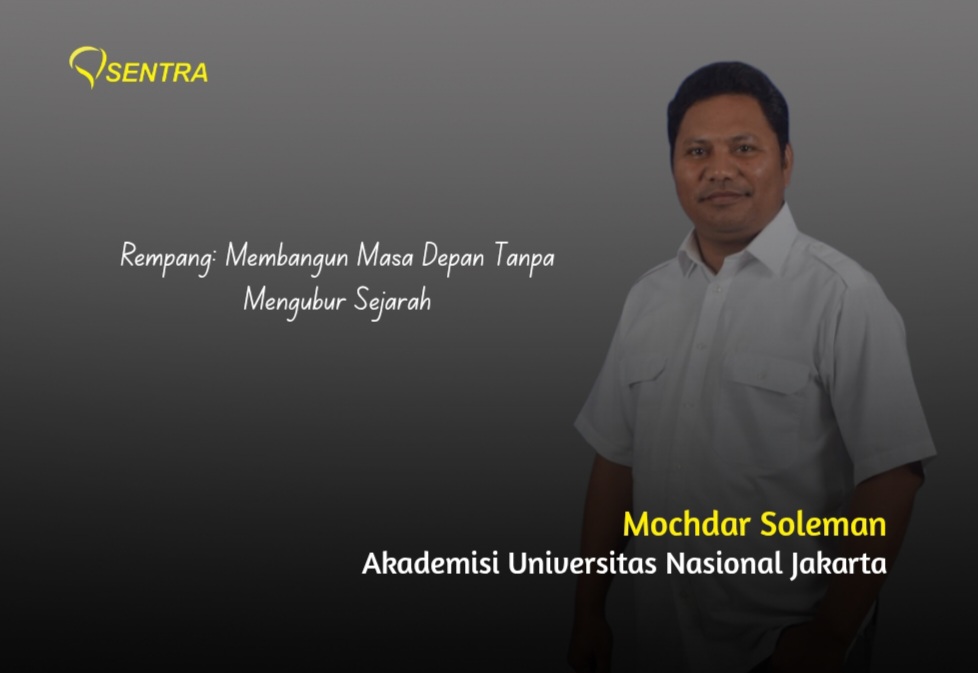Oleh:
Mochdar Soleman (Dosen dan Pengamat Politik Lingkungan, Universitas Nasional, Jakarta)
Pulau Rempang, sebuah wilayah di selatan Pulau Batam, mendadak menjadi titik api dalam peta konflik agraria nasional. Sejak diumumkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pulau ini menjadi sorotan media, aktivis, hingga lembaga hak asasi manusia. Di balik wacana pembangunan dan investasi yang menggiurkan, Rempang menyimpan luka struktural yang tak boleh diabaikan: penggusuran warga adat, pengingkaran sejarah, dan kekerasan yang merusak legitimasi negara.
Proyek Rempang Eco-City yang dikembangkan oleh BP Batam dan mitra investor asing bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai pusat industri energi baru terbarukan dan pariwisata kelas dunia. Namun, keberadaannya justru memicu resistensi warga yang telah tinggal di sana selama lebih dari satu abad. Mereka bukan pendatang gelap, melainkan pemilik sah dari 45 kampung tua yang telah tercatat dalam sejarah, budaya, dan bahkan dalam regulasi resmi negara.
Sejarah yang Diabaikan
Rempang bukanlah pulau yang tidak berpenghuni seperti yang kerap dideskripsikan dalam peta pembangunan. Kampung-kampung tua di Rempang telah berdiri sejak abad ke-19, jauh sebelum konsep tata ruang modern diterapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 52 Tahun 2014, eksistensi kampung tua ini diakui secara hukum sebagai bagian dari hak pengelolaan tradisional masyarakat adat Melayu. Mereka memiliki sistem sosial, struktur kepemimpinan, hingga norma lokal yang hidup dan berlangsung lintas generasi.
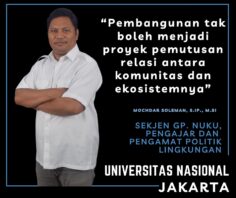
Namun, fakta sejarah ini seperti tak berarti dalam praktik kebijakan. Pemerintah Kota Batam, yang semestinya menjadi pelindung hak warganya, justru menolak memberikan pengakuan atas tanah-tanah adat tersebut. Ketika legalitas adat berbenturan dengan kehendak proyek nasional, yang dikorbankan adalah sejarah dan manusia.
Padahal, konstitusi kita menjamin pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sayangnya, asas ini menjadi pepesan kosong ketika implementasi kebijakan tidak menjadikannya acuan.
Kekerasan dalam Pembangunan
Sejak awal 2023, Rempang menjadi lokasi bentrokan antara warga dan aparat. Pada 7–11 September 2023, kekerasan meledak setelah warga menolak relokasi dan penggusuran paksa. Komnas HAM mencatat sejumlah pelanggaran prosedural dalam proses pemindahan. Setidaknya 15 orang mengalami luka-luka, termasuk anak-anak, dan sejumlah sekolah dirusak oleh gas air mata dan aparat yang memasuki ruang pendidikan tanpa izin. Tragedi ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis. Ini adalah bentuk kekerasan struktural.
Menurut Hamzah Ali, kajian akademik dari Universitas Negeri Jakarta, (edura.unj.ac.id) penggusuran massal terhadap sekitar 7.500 warga merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Pemindahan paksa yang dilakukan tanpa kesepakatan, tanpa kompensasi yang adil, dan tanpa dialog substantif melanggar prinsip-prinsip dasar UUPHAM (Undang-Undang Penghapusan Pelanggaran HAM Berat) dan Basic Principles on the Rights of Indigenous Peoples yang dikeluarkan oleh PBB.